
Pancasila
Bagian ini khusus membahas pandangan-pandangan berupa tulisan baik dari dosen maupun mahasiswa atau masyarakat umum berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar dan filosofi kebangsaan Negara Indonesia.
-
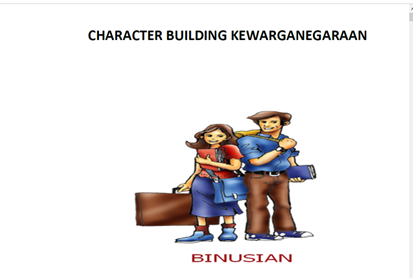
Character Building Kewarganegaraan
Modul Materi Ajar Character Building Kewarganegaraan (PPA BCA) read more
Yustinus Suhardi Ruman • October 10, 2024
-
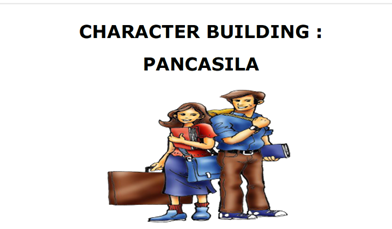
Modul Ajar Character Building Pancasila
Modul Materi Ajar Character Building Pancasila read more
Yustinus Suhardi Ruman • October 09, 2024
-
-
Naskah Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila 2020
Kajian Akademis Pengembangan PPP read more
• February 16, 2022
-
Aplikasi Game Pancasila untuk Meningkatkan Nasionalisme Generasi Muda di Tengah Covid*
Oleh: Talia Atara, Mahasiswa Binus University, NIM : 2440093053 Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam. Rasa nasionalisme dan persatuan tentunya merupakan hal yang sangat penting patut dijaga demi keutuhan bangsa Indonesia. Namun menjaga keutuhan bangsa tentu tidaklah mulus. Kerikil tajam radikalisme dapat mengarahkan kita ke jalan yang salah dan sikap intoleransi yang menyebabkan konflik horizontal di antara anak bangsa. Isu-isu yang membahayakan persatuan bangsa Indonesia seringkali disebabkan oleh pemahaman salah, artikel hate speech, atau bahkan berita-berita yang tidak benar alias hoax. Pandemi COVID-19 saat ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Penggunaan gadget meningkat selama masa pandemic merupakan fakta tak tersangkalkan. Hal ini tentunya membuat masyarakat khususnya kaum muda milenials semakin aktif menggunakan sosial media. Banyak hal tidak benar yang dapat diakses oleh masyarakat apalagi anak muda yang masih labil. Kesalahpahaman dapat terjadi jika generasi muda hanya melihat suatu hal dari satu sisi melalui sosial media. Dari suatu kesalahpahaman mengenai suatu hal, radikalisme dan rasa intoleransi juga dapat terjadi. Menurut KBBI, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Radikalisme dapat terjadi karena kurangnya pemahaman kritis dan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Tantangan yang dapat kita hadapi saat ini adalah sikap intoleransi yang terjadi karena kurang kuatnya spirit nasionalisme kita. Oleh sebab itulah, maka rasa nasionalisme sangat penting untuk ditingkatkan di tengah masyarakat terutama pada diri generasi muda penerus bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya di dalamnya. Negara Indonesia memiliki ribuan pulau yang terpisah oleh daratan dan lautan. Hal-hal tersebut membuktikan kekayaan dan keberagaman negara Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan hal yang patut dibanggakan. Akan tetapi, adanya keberagaman terkadang membawa masyarakat ke dalam perpecahan yang dapat menimbulkan berbagai konflik horizontal. Perbedaan-perbedaan yang seharusnya memperkaya, terkadang malah menjadi musibah bagi kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa di mana corona virus menyebar dan membuat masyarakat harus lebih banyak berdiam di rumah. Kondisi pandemi Covid-19 ini dapat menambah kemungkinan terjadinya konflik pada waktu yang tidak tepat. Hal ini dapat terjadi karena kesalahpahaman yang lebih mudah terjadi di media sosial. Pandemi ini tentunya menambah aktivitas online masyarakat khususnya dalam konteks kita di Indonesia. Meningkatnya aktivitas online, tentunya dapat menyebabkan peningkatan penggunaan media sosial juga. Peningkatan penggunaan media sosial cenderung terjadi di kalangan generasi muda Indonesia. Penggunaan media sosial dengan rasa peduli dan pengetahuan terhadap negara yang kurang, dapat menjadi hal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak kesalahpahaman yang dapat terjadi dari sebuah foto atau cuplikan yang ada di video, jika hanya dilihat dari satu sisi. Radikalisme, sikap intoleransi, hate speech, dan hoax dapat terjadi karena suatu kesalahpahaman di antara anak bangsa ini. Generasi muda yang sedang berada pada fase pencarian identitas dan jati diri serta eksistensi pribadi (di antara umur 17 hingga 24 tahun) rentan akan penyebaran radikalisme melalui sosial media. Apalagi jika kurang adanya sikap kritis dan filter etis yang baik. Hal ini diungkapkan oleh Wawan Hari Purwanto, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN). Penyebaran radikalisme yang terjadi dapat semakin meluas apabila rasa nasionalisme tidak diperkuat. Sikap intoleransi juga dapat menyebar melalui jejaring media sosial. Foto atau video yang menyerang suku, budaya, ras, atau agama tertentu dapat menyebabkan tumbuhnya sikap intoleransi. Generasi muda yang aktif bersosial media pun dapat terkena dampak dari hal tersebut. Kesalahpahaman mengenai suatu suku, budaya, ras, atau agama dapat memunculkan rasa tidak suka (dislike) yang berakhir pada sikap intoleransi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada generasi muda yang ikut menyebarkan sikap intoleransi kepada generasi muda lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidakpedulian terhadap bangsa Indonesia. Ujaran kebencian atau hate speech juga dapat muncul di kalangan generasi muda. Berdasarkan Wikipedia, ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran-ujaran kebencian itu dapat dengan mudah terekspos di media sosial. Terdapat beberapa generasi muda yang menyerap suatu informasi dengan mudah tanpa benar-benar memahami tentang hal yang ia serap. Apalagi, di media sosial orang sering hanya melihat dari salah satu sudut pandang saja, maka hal tersebut tentunya dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang semakin intens. Kesalahpahaman yang tidak teratasi dengan arif dan bijak dapat berakibat pada perpecahan antar kelompok dan golongan di dalam masyarakat Indonesia. Berita hoax merupakan hal yang tidak kalah penting untuk dibahas. Menurut Wikipedia, berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita sejenis ini merupakan hal yang saat ini banyak menyebar di masyarakat. Belum lagi karena semakin banyak orang yang menggunakan media sosial, berita hoax menjadi lebih mudah tersebar. Penyebaran berita semacam ini tentunya buruk bagi keberlangsungan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia, karena hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa. Tidak sedikit generasi muda yang ikut andil dalam pembuatan dan penyebaran berita hoax. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya rasa peduli terhadap persatuan Indonesia yang dapat diartikan sebagai kurangnya rasa nasionalisme. Untuk mengatasi hal ini, spirit nasionalisme tentunya penting untuk diperkuat agar masalah yang berkaitan dengan rasa nasionalisme dapat teratasi. Jika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kita pasti menjadi lebih peduli terhadap negara kita. Kepedulian terhadap negara dapat ditunjukkan melalui rasa semangat kita untuk mempelajari lebih dalam mengenai negara kita. Mengetahui lebih dalam mengenai negara kita tentunya dapat menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam tubuh bangsa ini. Pengetahuan yang mendalam membuat kita lebih memahami tentang apa yang benar dan tidak benar untuk dilakukan di dalam praksis kehidupan kita sehari-hari khususnya anak muda milenial. Pentingnya Peningkatan Rasa Nasionalisme Generasi Muda Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Keberlangsungan suatu negara dapat dikatakan juga bergantung pada rasa nasionalisme dari masyarakatnya. Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam orang di dalamnya yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, dan kepercayaan pastinya sangat memerlukan rasa persatuan. Rasa persatuan dapat timbul dari jiwa nasionalisme yang kuat. Jika seseorang memiliki rasa nasionalisme yang kuat, ia akan berusaha untuk menjaga keutuhan dan kesatuan dari bangsa dan negara Indonesia. Rasa nasionalisme sudah seperti hal yang wajib dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia terutama karena adanya suatu fakta yang tidak terbantahkan adanya bahwa kita beragam adanya. Rasa nasionalisme tentunya perlu untuk dikembangkan dan ditumbuhkan di berbagai generasi di Indonesia karena nasionalisme ini harus terus ada selama kita menjadi warga negara untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Tindak kriminal juga dapat berkurang jika masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat akan berusaha untuk juga menjaga keamanan dan kedamaian di dalam negara. Generasi muda terutama yang sedang berada pada fase pencarian jati diri tentunya sangat penting untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tiggi akan lebih sulit terjerumus ke dalam hal yang buruk, karena rasa pedulinya terhadap negara lebih tinggi. Dengan tingkat kepedulian yang lebih tinggi, kita menjadi lebih berhati-hati sebelum melakukan suatu hal yang buruk secara moral. Persoalan radikalisme yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dapat terjadi karena kurangnya rasa nasionalisme. Dapat kita lihat, tindak radikalisme memecah persatuan antar masyarakat, kelompok, atau golongan tertentu. Jika seseorang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, ia dapat lebih memahami mana hal yang baik untuk diikuti dan mana yang tidak. Radikalisme telah menyebabkan kepanikan psikologis di tengah masyarakat berdampak pada rusaknya keamanan dan kedamaian suatu negara. Generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, akan melakukan riset atau kajian kritis terhadap paham-paham yang ada agar tidak terjerumus ke dalam perilaku buruk yang dapat menyebabkan perpecahan. Sikap intoleransi juga dapat terjadi karena kurangnya rasa nasionalisme. Sikap intoleransi seperti tidak menghargai budaya atau agama yang dimiliki oleh sesama warga negara menjadi salah satu faktor pemecah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi dapat meningkatkan sikap toleransi antar suku, ras, budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan paham mengenai nilai-nilai Pancasila dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ia juga akan setia menghayati nilai-nilai Pancasila itu di dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan praktis sehari-hari. Permasalahan lain yang dapat terjadi dari kurangnya rasa nasionalisme adalah penyebaran artikel hate speech. Artikel yang berisi ujaran kebencian merupakan artikel yang tidak baik untuk tersebar di dunia maya. Generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi pastinya lebih dapat melihat hal negatif tersebut dan tidak memperluas penyebarannya. Penyebaran berita hoax terjadi karena kurangnya rasa nasionalisme. Penyebaran berita bohong ini menyebabkan persepsi yang salah tentang seseorang, kelompok, atau bahkan negara. Seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi tentunya lebih peduli terhadap hal-hal tersebut dan lebih mengecek kebenaran beritanya terlebih dahulu atau fact cheking sebelum memutuskan untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Oleh karena hal-hal tersebut, rasa nasionalisme masyarakat Indonesia terutama generasi muda perlu ditingkatkan. Dilansir dari beritasatu.com, Komjen Suhardi Alius selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa teknologi informasi yang semakin maju membuat identitas bangsa Indonesia terutama generasi muda semakin berkurang karena adanya macam-macam paham yang tidak baik termasuk radikalisme dan terorisme. Suhardi kemudian mengatakan suatu hal mengenai wawasan kebangsaan, “Fakta itulah yang membuat saya tidak pernah lelah memberikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda, terutama mahasiswa. Ini panting mereka adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia. Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir nanti akan banyak terjadi pengaruh buruk yang akan merusak bangsa dan negara ini.” Aplikasi Game Pancasila untuk Meningkatkan Nasionalisme Generasi Muda Aplikasi Game Pancasila yang dimaksud berupa game edukasi yang berisi permainan pengetahuan. Game sejenis ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terutama generasi muda. Edukasi melalui game dipercaya dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif karena lebih menyenangkan. Belum lagi di tengah pandemic COVID – 19 sebagian masyarakat menjadi lebih sering menggunakan gadget. Aplikasi game yang dapat dengan mudah diakses melalui gadget tentunya dapat menjadi suatu solusi yang menarik untuk dicoba karena kita tidak hanya mendapatkan kesenangan dari bermain game namun juga pengetahuan yang memperkaya wawasan kebangsaan. Metode pembelajaran yang menyenangkan dapat diterapkan sedari kecil. Alangkah baiknya jika rasa nasionalisme dapat dikembangkan sejak keciil karena tentunya sesuatu yang ditanamkan dari kecil akan lebih sering diingat sampai dewasa. Metode pembelajaran yang menyenangkan seperti ini juga dapat digunakan oleh orang-orang dari berbagai kalangan umur termasuk generasi muda. Semakin kita mengenal mengenai dasar negara kita, Pancasila, rasa nasionalisme kita dapat semakin kuat dan memberikan efek yang sangat positif bagi peningkatan wawasan kebangsaan kita. Pengenalan pada dasar negara kita, Pancasila, dapat menjadi hal penting dalam memperkuat rasa nasionalisme. Hal itu dikarenakan semakin kita mengenal dasar negara kita, semakin kenal pula kita dengan budaya-budaya yang ada di negara kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran dari para founding fathers yang peduli akan keberlanjutan negara Indonesia ini. Mempelajari lebih dalam mengenai dasar negara kita tentunya memperdalam rasa cinta kita terhadap tanah air dan negara Indonesia tercinta ini. Bertambah dalamnya rasa cinta terhadap tanah air kita, Indonesia, dapat memperdalam rasa nasionalisme yang kita miliki. Aplikasi game Pancasila mengandung konten sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila yang meliputi: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Melalui aplikasi game Pancasila, kita dapat menyalurkan gambar-gambar serta menunjukkan video-video yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara Indonesia sebagaimana yang mengkristal di dalam sila-sila Pancasila. Orang-orang yang sering melihat suatu gambar atau video yang menampilkan aksi-aksi positif juga dapat terbawa untuk mengikuti aksi positif tersebut. Game edukasi seperti game Pancasila dapat menjadi solusi yang lebih mudah untuk mengajak seseorang khususnya generasi muda untuk memperdalam pengetahuan mengenai negara kita Indonesia. Tentunya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi game Pancasila tersebut diperlukan, sehingga lebih bervariasi, kreatif, inovatif, dan inspiratif sehingga dapat digunakan di berbagai kalangan umur. Pandemi COVID – 19 membuat kita sulit untuk bertemu dengan orang lain secara langsung. Pembelajaran online yang berlangsung membuat kita lebih sulit untuk mencontohkan seperti apa sikap-sikap dan karakter-karakter yang baik untuk diterapkan sebagai warga negara Indonesia yang ideal. Aplikasi game Pancasila ini tentunya dapat membantu memberikan contoh-contoh tersebut. Tantangan pembelajaran online ini dapat menjadi salah satu peluang untuk menggunakan game Pancasila sebagai salah satu alat bantu pembelajaran terutama untuk pendidikan kewarganegaraan (civics education). * Artikel ini disarikan dari sebuah tulisan essay yang diikutsertakan dalam lomba menulis 10 Tahun NUNI 2021. Referensi: https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/20/124608765/waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia?page=all https://www.liputan6.com/news/read/4421736/jokowi-tidak-ada-tempat-untuk-terorisme-di-indonesia https://tirto.id/menilik-laku-intoleran-di-kalangan-siswa-dan-mahasiswa-f7xs https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian https://lifestyle.kompas.com/read/2017/09/22/161600620/remaja-rentan-jadi-penyebar-berita-hoax https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-pemerintah-tidak-akan-biarkan-sikap-intoleran-di-indonesia.html https://www.beritasatu.com/nasional/483071/generasi-muda-harus-kembalikan-jiwa-nasionalisme https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf https://news.detik.com/berita/d-4018990/dua-remaja-pengebom-gereja-di-surabaya-suka-maroon-five-dan-game https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/180000269/nasionalisme-arti-sejarah-dan-tujuan?page=all read more
• October 12, 2021
-
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN IPTEK
by: Ch. Megawati Tirtawinata Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi (inovasi teknologi canggih). Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu: Dimensi Reality. Yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Dimensi Idealisme. Yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Dimensi Fleksibility. Maksudnya dimensi pengembangan Ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Pada umumnya para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatarbelakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan IPTEK dan masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif dan efektif, ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan Nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatakan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis IPTEK tanpa kehilangan jati diri (nilai-nilai Pancasila). Hal ini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekular dunia Barat, yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, sepertinya berjalan berlawanan. Dalam masyarakat modern yang berbasisi IPTEK, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi, ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting, karena landasan moral, segenap imperative moral, dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, adalah keimanan dan ketakwaan. Konsep Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas, rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral (etika). Atas dasar kreatifitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Mahaesa. Oleh karena itu tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Sila Ketuhanaan yang Mahaesa. Sila ini mengklomentasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia disekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagi pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Contoh perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan yang maha esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi kloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kotroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya “intervensi penciptaan” yang semestinya dilakukan oleh Tuhan YME. Bagi yang beragama muslim, pada surat An-naazi’aat ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. “apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?”, mereka berkata “kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi”. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan manusia namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila persatuan Indonesia Mengklomentasikan universal dan internasionalisme (kemanusiaan) dr sila-sila lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Artinya mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu dalam pengembangan IPTEK setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan oranglain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan IPTEK dewasa ini sangat pesat, dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini manusia tak dapat hidup tanpa bantuan teknologi. Di samping dampak positif terdapat juga dampak negatif dari perkembangan kemajuan IPTEK. Pelanggaran IPTEK pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan perkembangan IPTEK di Indonesia sepenuh-penuhnya sesuai dengan Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat, berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan pedamaian. Oleh karena itu perkembangan IPTEK di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia ,yaitu Pancasila: 1. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Perkembangan IPTEK karena Nilai-nilai pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan Nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Referensi: 1. https://www.academia.edu/38145256/PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_PENGEMBANGAN_IPTEK_DAN_IMPLEMENTASI_DALAM_IKM?email_work_card=view-paper 2. Diktat CB Pancasila (CHAR0613) oleh Tim CBDC, tidak diterbitkan read more
• February 03, 2021
-
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI MOTIVATOR DAN PARADIGMA PERKEMBANGAN IPTEK
by: Ch. Megawati Tirtawinata Nilai-nilai Pancasila Sebagai Motivator Perkembangan IPTEK Secara konstitusional kedudukan nilai filsafat Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara; sekaligus sebagai asas kerohanian negara dan sebagai perwujudan jiwa bangsa. Dengan demikian, identitas dan integritas (nasional) Indonesia ialah nilai filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi sumber motivasi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nasional dalam mencerdaskan bangsa. Nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, secara filosofis-ideologis dan konstitusional, NKRI dapat dinamakan (dengan predikat) sebagai sistem kenegaraan Pancasila yang sejajar dan analog dengan berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa lain. Kedudukan nilai Pancasila (sistem ideologi Pancasila) dengan demikian berfungsi juga sebagai asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya, moral dan politik nasional, sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi yang memandu kehidupan bangsa Indonesia dalam integritas NKRI sebagai sistem kenegaraaan Pancasila. Maknanya, integritas nilai Pancasila secara konstitusional imperatif memberikan asas budaya dan moral politik nasional Indonesia serta membangun bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan menguasai berbagai teknologi (IPTEK) guna memenuhi kehidupan masyarakat. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil kreatifitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan yang Mahaesa. Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat read more
• February 03, 2021
-
WALZER, PLURALISME DAN KEADILAN
Oleh: Iqbal Hasanuddin Michael Walzer (1935-) adalah seorang filsuf politik asal Amerika Serikat yang beraliran komunitarianisme atau komunitarisme. Sebagai komunitaris, ia menolak pandangan kaum liberal seperti John Rawls dan Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa ada suatu prinsip universal untuk mengelola sebuah masyarakat agar menjadi sebuah masyarakat yang adil. Misalnya, Rawls menyebut "dua prinsip keadilan," sementara Dworkin menyebut prinsip "kesetaraan sumberdaya." Dalam buku Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (1983), Walzer mengemukakan pandangannya tentang keadilan yang agak berbeda dari pandangan umumnya dalam kajian-kajian filsafat politik. Biasanya, seperti Rawls atau Dworkin di atas, para faylasuf politik akan mencari aksioma atau prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pendasaran di balik berbagai kepercayaan dan pandangan yang lebih nyata ihwal tindakan atau tatanan masyarakat yang adil; hak, perlakuan yang setara, kelayakan, dll. Pandangan Walzer tentang keadilan tidak berpijak pada satu prinsip baku, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda, tergantung pada masyarakatnya, waktu, tempat dan barang-barang yang dianggap perlu didistribusi. Dengan kata lain, pendekatan Walzer terhadap keadilan bersifat majemuk atau pluralistik. Karenanya, istilah pluralisme dan keadilan sering dilekatkan oleh komentator kepada karakteristik pemikiran politik Walzer. Selain mengakui pendekatannya yang bersifat pluralistik terhadap persoalan keadilan, Walzer mengemukakan istilah lain untuk menjelaskan pandangan politiknya: Kesetaraan majemuk (complex equality). Di sini, ia mengakui bahwa masyarakat manusia pada hakikatnya adalah sebuah komunitas untuk berbagi. Dalam masyarakat, setiap orang menciptakan barang atau jasa, berbagi dan saling bertukar satu sama lain. Bahkan, pekerjaan itu sendiri dibagi-bagi di antara anggota masyarakat dalam bentuk pembagian kerja. Menurut Walzer, tidak ada pola tunggal dalam pembagian barang atau jasa tersebut. Dalam pandangan Walzer, gagasan keadilan distributif banyak terkait dengan tatanan politik yang berbeda-beda, landasan ideologi yang berbeda-beda pula, dan konsep keanggotaan komunitas yang berbeda-beda pula. Misalnya, pola pembagian yang adil terkait layanan kesehatan atau pendidikan untuk anggota komunitas tidaklah sama di antara negara-kota Athena pada 5 Abad sebelum Masehi, komunitas Yahudi-Mesir di Abad Tengah, dan rezim "negara kesejahteraan" Amerika Serikat di Abad ke-20 dan 21 Masehi. Intinya, tidak ada pola baku dan sama yang berlaku lintas-waktu dan tempat. Walzer berpandangan bahwa keadilan telah senantiasa tersituasikan (situated) dalam masyarakat tertentu. Karenanya, keadilan tidak terkait dengan prinsip-prinsip universal, melainkan sesuatu yang kongkret, yang sesuai dengan struktur kenyataan dan masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini, penilaian atas adil atau tidaknya sebuah masyarakat tidak bisa dilakukan dari luar, melainkan memahaminya dari dalam masyarakat itu sendiri. Jika pemahaman anggota masyarakat itu berbeda-beda tentang apa itu adil, maka perbedaan-perbedaan itu harus dimunculkan, tidak boleh ditekan, didialogkan bersama di antara anggota komunitas atau masyarakat yang bersangkutan. Walzer juga berpandangan bahwa pola pembagian yang adil berbeda-beda seiring dengan perbedaan karakteristik dan jenis barang-barang yang dibagikan: Keamanan, kesehatan, uang, komoditas, pemerintahan, pekerjaan, hari libur, pendidikan, keluarga, cinta, berkah ilahi, penghargaan dan kekuasaan politik. Di antara barang-barang publik tersebut, ada yang dibagi-bagikan dengan mempertimbangkan asas siapa yang membutuhkan, siapa yang pantas atau siapapun yang mau dan bisa dalam pertukaran bebas. Tidak semua barang-barang publik itu bisa diperjualbelikan melalui mekanisme pasar. Tentang hal ini, terdapat istilah yang menarik dari Walzer dan para pemikir komunitarian lainnya: Tirani. Istilah ini mengacu kepada ketidaksesuaian antara kriteria pembagian dan barang-barang publik yang dibagikan. Misalnya, prinsip meritokrasi cocok untuk dijadikan dasar pemberian reward & punisment untuk orang-orang yang bekerja di lingkungan perusahaan maupun lembaga-lembaga pemerintah. Tapi, prinsip meritokrasi tidak tepat dipakai untuk pengelolaan kehidupan politik masyarakat, layanan kesehatan dan pendidikan. Karenanya, itu akan menjadi "tirani presentasi" jika prinsip itu dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai. Selain itu, juga ada istilah "tirani uang" jika barang-barang publik yang tidak seharusnya diperjualbelikan tapi justru diperjualbelikan melalui mekanisme pasar. read more
• February 02, 2021
-
Teori Kebebasan Isaiah Berlin
Oleh: Iqbal Hasanuddin Isaiah Berlin (1909-1997) adalah seorang filsuf politik yang banyak berbicara tentang teori kebebasan. Dalam hal ini, Berlin membedakan dua konsep kebebasan, yaitu: kebebasan positif (bebas untuk) dan kebebasan negatif (bebas dari). Bagi Berlin, kebebasan yang diperjuangkan dalam rumusan filsafat politikya adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif. Menurut Berlin, konsep kebebasan positif (bebas untuk) adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut. Sementara itu, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif (bebas dari) adalah pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun. Di sini, kata "negatif" memiliki konotasi logika (tidak/bukan), bukan konotasi moral (baik atau buruk). Artinya, "kebebasan negatif" adalah konsep kebebasan yang menekankan pentingnya untuk "tidak dipaksa." Berlin mendorong kita untuk mewaspadai konsep kebebasan positif (bebas untuk). Sebab, dalam konsep kebebasan positif ini, fokus utamanya adalah bagaimana saya dapat mewujudkan apa yang saya harapkan. Di dalamnya, terdapat kemungkinan bagi saya untuk menjadikan orang lain seperti sarana atau alat untuk mencapai tujuan saya itu. Dalam konsep kebebasan positif ini, tidak ada jaminan bahwa orang lain akan terbebas dari paksaan. Sebaliknya, Berlin menegaskan pentingnya dukungan bagi konsep kebebasan negatif (bebas dari paksaan). Dalam konsep ini, terdapat jaminan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang akan dipaksa untuk melakukan sesuatu demi melayani tujuan dan kepentingan orang lain. Istilah lain untuk menyebut kebebasan negatif ini adalah otonomi. Dalam hal ini, Berlin mendukung otonomi manusia, serta menolak heteronomi (dalam bentuk paksaan dari luar untuk melakukan sesuatu). Kewaspadaan Berlin terhadap konsep kebebasan positif berbanding lurus dengan sikap kritisnya terhadap model berpikir a la rasionalisme Pencerahan. Bagi Berlin, ada keangkuhan dalam rasionalisme Pencerahan di mana sang subyek Pencerahan dianggap bisa memahami kenyataan secara rasional dan menata dunia menurut standar rasionalitas tertentu. Pada gilirannya, ini berpotensi untuk mengerus keragaman cara pandang orang lain di mana keragaman ini sebetulnya tidak bisa diluluhkan dengan satu standar rasionalitas tertentu atau milik seseorang. read more
• February 02, 2021
